Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama
Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama
Oleh : Nadzirotus Sintya Falady, S.H.
CPNS Analis Perakara Peradilan (Calon Hakim) 2021 Pengadilan Agama Probolinggo
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan manusia, perkawinan dan kelahiran anak merupakan peristiwa besar
yang menimbulkan akibat hukum kompleks yang akan terus melekat pada diri manusia tersebut hingga mati. Indonesia sebagai Negara Hukum,[1] telah menjamin dan melindungi pemenuhan hak konstitusional perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi aturan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
(1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”
(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dari perkawinan yang sah inilah, kewajiban dan hak-hak yang timbul setelah adanya perkawinan tersebut dapat dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh Negara. Salah satu tujuan umum yang ingin digapai dalam kehidupan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Hakikatnya anak adalah amanah dan karunia ALLAH SWT yang senantiasa wajib diijaga, karena dalam dirinya melekat hak asasi manusia yang merupakan anugerah dari ALLAH SWT.[2] Amanat Konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur bahwa :
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Namun fakta mengatakan lain, sebab fenomena kelahiran anak diluar perkawinan, hingga kini masih marak dijumpai. Kadangkala ada pasangan yang telah melakukan perkawinan sah secara agama, syarat dan rukunnya telah dipenuhi sesuai ketentuan Hukum Islam, tetapi tidak mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga apabila lahir anak dari perkawinan tersebut, maka tidak mendapat kekuatan hukum di mata Negara. Peristiwa semacam ini lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “Nikah Siri”.
Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa Nikah Siri, diantaranya[3] :
- Kedua belah pihak memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga tidak/belum punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA;
- Terhalang aturan yang melarang poligami (nikah lebih dari satu);
- Kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum siap karena masih sekolah/ kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu;
- Kedua atau salah salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa;
- Terpaksa menikah siri karena tertangkap basah berzina, maka untuk menutup aib dilakukanlah nikah siri;
- Terdorong keinginan nafsu sesaat, agar terhindar dari perzinahan maka dilakukanlah nikah siri.[4]
Perkawinan dibawah tangan (Nikah Siri) biasanya dilaksanakan berdasarkan syariat agama atau adat istiadat calon mempelai. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut memang dapat dikatakan sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara, dengan kata lain nikah siri tersebut dianggap tidak pernah ada. Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Istri tidak mendapatkan hak waris dari suami yang telah meninggal, dan apabila terjadi perceraian, maka tidak akan mendapat hak nafkah maupun harta gono-gini. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut pun tidak dianggap anak sah.[5] Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
Anak yang sah memiliki hak keperdataan yang sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hak keperdataan yang dimaksud meliputi :
- Hak nasab anak yang akan dihubungkan kepada ayah dan ibu;
- Hak pemberian nafkah terhadap anak;
- Hak pemeliharaan dan pendidikan anak (Hadhanah);
- Hak saling mewaris dengan orang tuanya;
- Dalam akta kelahirannya berhak dicantumkan nama ayahnya melalui mekanisme Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Hak perwalian nikah dari ayah bagi anak perempuan; dan hak-hak keperdataan lainnya.
Anak yang sah sebagaimana ketentuan pasal tersebut, secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya. Apabila seorang suami mengingkari/menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, dan dapat dibuktikan bahwa isitrinya benar telah berzina, maka suami tersebut dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Dan jika dalam pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, sehingga jelas bahwa kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan.[6]
Selain anak yang sah dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dikenal pula status anak yang lahir di luar perkawinan. Untuk memahami pengertian anak luar kawin, diperlukan penafsiran berdasarkan logika argumentum a contrario terhadap rumusan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dapat diambil pengertian sebaliknya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak luar kawin, yang mencakup anak yang lahir dari pernikahan siri dan anak yang lahir akibat perbuatan zina. Lebih lanjut, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Namun eksistensi pasal ini dianulir dengan hadirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, sehingga Pasal 43 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan meniadakan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hal ini berarti, anak luar kawin akan dikategorikan sebagai anak yang sah apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Lazimnya, pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dilakukan dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (Deoksiribo Nuklead Acid). Melalui hasil tes DNA akan diketahui apakah ada kesamaan golongan darah antara ayah dengan anak atau tidak. Tes DNA dapat dilakukan baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (li’an), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.
Oleh karena itu Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dimaknai :
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .”[7]
Mengutip pendapat Chatib Rasyid (Mantan Ketua PTA Semarang), anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.[8] Hal ini menunjukkan adanya perkawinan sah secara materiil berdasarkan hukum islam dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan, sebelum anak tersebut dilahirkan,. Namun karena perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan baik di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam maupun di Kantor Pencatatan Sipil bagi non Islam, maka pernikahan tersebut secara formil dapat dikatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.[9] Sehingga dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Hal ini karena frasa “Anak diluar perkawinan” sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bukanlah merupakan anak hasil zina, tetapi anak yang lahir dari nikah siri. Mengutip klarifikasi Mahfud M.D (Ketua Mahkamah Konstitusi pada masa itu), yang menyatakan bahwa :
“yang dimaksud majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan.[10]
Sehingga jelas bahwa hubungan perdata yang diberikan kepada anak diluar perkawinan (nikah siri) tidak bertentangan dengan syariat islam terkait nasab, wali nikah, dan waris.
Putusan MK tersebut tidak berlaku untuk anak hasil zina, karena perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, kedudukannya kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI. Sedangkan anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka. Walaupun dilahirkan akibat perbuatan zina, ia tetap dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa dari perbuatan kedua orang tuanya. Namun konsekuensinya, anak hasil zina hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dapat mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya.[11] Hal ini didasarkan karena dalam Hukum Islam, nasab merupakan salah satu elemen pokok dalam maqashid syari’ah[12] yang harus dijaga. Kemurnian nasab dalam hukum Islam memiliki peran vital sebab Hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam Islam.[13]
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI LUAR KAWIN
Dalam hukum positif Indonesia, diatur bahwa anak di luar kawin seharusnya mendapat perlindungan hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[14] Perlindungan anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
- nondiskriminasi;
- kepentingan yang terbaik bagi anak;
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- penghargaan terhadap pendapat anak.[15]
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :
“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa :
“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut.”
Adapun upaya hukum perlindungan anak yang dapat diupayakan oleh Pengadilan Agama dan sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu melalui :
- Permohonan Itsbat Nikah;
- Permohonan Penetapan Asal Usul Anak
PERMOHONAN ITSBAT NIKAH
Perkawinan siri (tidak tercatat) adalah perkawinan yang secara materiil telah memenuhi dan dilaksanakan berdasarkan hukum islam sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun secara formil tidak memenuhi aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu untuk dilakukan pencatatan. Agar perkawinan siri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.[16] Itsbat nikah atau yang lazim dikenal sebagai pengesahan nikah adalah perkara voluntair (permohonan) yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, namun tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.
Landasan yuridis yang menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang itsbat nikah adalah Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Namun di lain sisi, kedua aturan tersebut juga membatasi bahwa perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat ke Pengadilan Agama hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. Berdasarkan pembatasan tersebut, sebenarnya Pengadilan Agama tidak memiliki payung hukum untuk menjalankan kewenangannya secara optimal melakukan itsbat nikah. Sedangkan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terus meningkat seiring dengan kebutuhan persyaratan administrasi anak untuk berbagai keperluan. Misalnya persyaratan administrasi bahwa setiap anak wajib memiliki Akta Kelahiran[17], sedangkan salah satu persyaratan adminsitrasi yang harus dipenuhi untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran adalah buku nikah orang tua. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan mashlahah bagi umat Islam, bahwa itsbat nikah sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.[18]
Berdasarkan urgensi tersebut, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi aturan tersebut, dan mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”
maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanyalah dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun eksistensinya harus dimaknai sebagai hukum positif Islam yang dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama merupakan suatu bentuk kebijakan guna mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[19]
Suatu permohonan itsbat nikah yang dikabulkan, maka terhadap penetapan Pengadilan Agama tersebut dapat dijadikan dasar bagi pasangan suami istri untuk mengajukan penerbitan akta nikah atas nama yang bersangkutan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penetapan itsbat nikah ini berlaku sejak pernikahan siri tersebut dilakukan, bukan sejak permohonan itsbat nikah diajukan. Sehingga setelah akta nikah tersebut terbit, maka hak anak yang dilahirkan dari nikah siri untuk memiliki akta kelahirannya dapat diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat tanpa harus mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama.
Contoh :
- A dan B melakukan nikah siri tanggal 18 April 2006 di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Pada 07 Oktober 2010 lahir anak perempuan bernama C;
- Pada 20 Maret 2017 A dan B hendak mengurus Akta Kelahiran C ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan meminta agar C dinyatakan lahir dari suami istri A dan B tetapi oleh Disdukcapil ditolak karena tidak dapat melampirkan akta nikah A dan B;
- Pada 23 Maret 2017 A dan B mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Probolinggo;
- Setelah dilaksanakan pemeriksaan sesuai Hukum Acara ternyata terbukti A dan B telah menikah sesuai hukum islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pada 30 Maret 2017 majelis hakim menjatuhkan penetapan yang inti amarnya berbunyi “Menyatakan sah perkawinan antara A dengan B yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo”;[20]
- A dan B mengajukan penerbitan akta nikah kepada KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan melampirkan salinan penetapan itsbat nikah, kemudian KUA Kademangan menerbitkan akta nikah berdasarkan salinan penetapan tersebut, dimana tanggal pernikahannya yaitu tanggal 18 April 2006;
- Oleh karena C dilahirkan pada 07 Oktober 2010 (setelah pernikahan), maka berdasarkan akta nikah tersebut, A dan B dapat langsung mengajukan penerbitan akta kelahiran C pada Disdukcapil sesuai syarat dan prosedur yang berlaku. Jadi tidak memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- Akta kelahiran yang telah terbit, menjadi bukti otentik tentang asal usul anak tersebut.[21]
PERMOHONAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK
Dalam Hukum Islam penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan cara pengakuan (istilhaq) dan pembuktian (al bayyinah).[22] Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, penetapan asal usul anak diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
Pasal 55
- Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Kompetensi absolut terkait penetapan asal usul anak sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama di ranah perkawinan juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Penetapan asal-usul anak merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap anak. Dengan penetapan asal-usul anak, hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi. Penetapan asal-usul diajukan sebagai perkara voluntair, yakni permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa pihak lawan. Pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara voluntair yang lain dengan produk penetapan, bukan putusan. Dari penetapan Pengadilan Agama inilah yang menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.
Contoh :
- P dan Q melakukan nikah siri tanggal 18 April 2006 di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Pada 07 Oktober 2010 lahir anak laki-laki bernama R;
- Pada 01 Januari 2012 P dan Q melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat pada KUA Kecamatan Kademangan;
- Pada 15 Januari 2015 P dan Q hendak mengurus Akta Kelahiran R ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan meminta agar R dinyatakan lahir dari suami istri P dan Q tetapi oleh Disdukcapil ditolak karena alas hukum Akta Nikahnya menyatakan pernikahan tanggal 01 Januari 2012, sementara anaknya R lahir tanggal 07 Oktober 2010;
- Maka P dan Q harus mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama R tersebut pada Pengadilan Agama Probolinggo;
- Jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka majelis hakim akan menjatuhkan penetapan yang inti amarnya berbunyi “Menetapkan anak laki-laki yang Bernama R, lahir di Probolinggo, 07 Oktober 2010 adalah anak kandung dari P dan Q”;
- Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut, dapat diurus akta kelahiran anak R di Disdukcapil setempat
Permohonan penetapan asal usul anak juga dapat diajukan oleh pasangan suami istri yang melahirkan anak setelah pernikahan siri, namun tidak mengajukan permohonan itsbat nikah maupun akad nikah baru.
Penetapan asal usul anak di Indonesia masih menimbulkan banyak perdebatan utamanya terkait anak yang lahir karena perbuatan zina, yaitu akibat hubungan biologis perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam islam anak hasil zina tidak memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“… anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak ia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka, mereka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya…” (HR. Ahmad 7042, Abu Daud 2267, dihasankan Syuaib Al-Arnauth)
Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nafkah, wali nikah, dan waris dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Namun sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar terhadap anak hasil zina, sebagaimana telah ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 Nomor 11 tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan memenuhi kewajiban untuk :
- Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- Memberikan bagian dari harta peninggalan lelaki pezina pada anak yang lahir akibat perbuatan zinanya melalui mekanisme wasiat wajibah.[23]
Terminologi anak zina dalam literatur fikih disebut dengan anak zina (walad al-zinā), meskipun demikian dalam hukum Islam, anak hasil zina atau anak yang orang tuanya tidak diketahui sekalipun, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Hukumnya tetap sebagai anak yang harus diperlakukan sebagaimana anak yang lainnya. Menurut hukum islam, status kelahiran anak hanya dibedakan menjadi dua, yaitu :
- anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum/syariat;
- anak yang dilahirkan dari perbuatan zina atau yang dilahirkan selain yang disyari’atkan.
Perbedaan yang menyebabkan kelahiran anak, tidak berakibat anak itu menjadi anak sah atau anak tidak sah, melainkan berakibat terhadap nasab anak tersebut, anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, nasabnya dihubungkan terhadap kedua orang tuanya, serta keluarga kedua belah pihak secara sempurna, sementara anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina di luar ikatan perkawinan, nasabnya hanya dihubungkan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana ketentuan syariat islam, pendapat mayoritas ulama dan juga sebagaimana telah diatur dalam pasal 100 KHI.[24] Hubungan ini bersifat alamiah dan tidak dapat disangkal, karena ibunyalah yang telah mengandung dan melahirkan anak tersebut. Sedangkan ayahnya, sulit diidentifikasi karena bisa saja yang melakukan hubungan dengan ibunya lebih dari satu orang.
Berkaitan dengan lapangan Pengadilan Agama, masih banyak ditemui ragam disparitas putusan Pengadilan Agama tentang asal-usul anak, sehingga berimplikasi pada beragamnya perlindungan anak hasil zina. Putusan Pengadilan Agama yang beragam tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok yaitu :
- Pertama, putusan yang menolak permohonan penetapan asal-usul anak (Penalaran Hukum Hakim Pragmatis)
Penetapan ini sama sekali tidak mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum bagi anak zina. Ditolaknya pengakuan anak oleh orang tuanya berakibat pada tidak adanya perlindungan hak asasi anak dan jaminan kesejahteraan bagi anak dari orang tuanya. Penetapan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan hakim ini juga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut menjadikan hakim dinilai tidak dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.
- Kedua, putusan yang menetapkan status anak zina sebagai anak ibu dan ditolaknya permohonan pengakuan anak oleh ayah biologis (Penalaran Hukum Hakim Konserfatif)
Penetapan yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam ini dinilai penulis kurang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak zina, karena hanya memberikan perlindungan kepada anak zina sebatas pada adanya hubungan hukum antara anak dan ibunya. Konsekuensi hukumnya adalah identitas anak yang dituangkan dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya. Karena anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, maka hak-hak anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan kewarisan hanya dapat diperoleh dari ibunya. Apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin fikih, maka penetapan ini dapat dianggap benar. Akan tetapi putusan tersebut dipandang kurang memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak zina jika ditinjau dari kacamata Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena putusan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial-psikologis bagi anak. Anak zina akan hidup terlantar dan mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai anak haram atau anak zina. Sehingga anak tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik yang berakibat pada kurangnya rasa percaya diri.[25]
- Ketiga, putusan yang mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak zina dan memberikan hubungan keperdataan terbatas (tidak sempurna) dengan ayahnya (Penalaran Hukum Hakim Progresif)
Putusan ini merupakan terobosan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak zina. Dikabulkannya permohonan pengakuan anak oleh kedua orang tuanya merupakan pemberian kejelasan asal-usul anak dan kepastian hukum tentang adanya hubungan keperdataan antara si anak dan kedua orang tuanya. Namun hal ini sebatas berupa tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan memberikan harta peninggalan melalui wasiat wajibah agar kesejahteraan anak dapat terjamin sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012. Kewajiban tersebut merupakan sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak di luar nikah karena telah melanggar norma hukum agama dan negara (berzina). Pemberlakuan sanksi tersebut mengandung tiga tujuan : Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak biologis. Kedua, sebagai perlindungan terhadap anak biologis agar dapat hidup secara layak. Ketiga, sebagai efek jera bagi pelaku zina, sehingga dapat meminimalisir praktik perzinaan di masyarakat.[26] Menurut pandangan penulis, penetapan semacam inilah yang dapat menjadi solusi terbaik bagi permasalahan rumit anak yang lahir dari perbuatan zina. Karena, tidak adil jika seorang anak biologis harus kehilangan asal-usulnya dengan ayah dan hak-hak keperdataan yang seharusnya diperoleh karena dosa orang tuanya. Meskipun hak keperdataan yang hanya terbatas pada pemenuhan nafkah dan wasiat wajibah, dan tetap memperhatikan hukum islam bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dan wali nikah dengan ayahnya, setidaknya anak tetap terhubung dengan ayah biologisnya, serta ibu yang melahirkannya pun tidak menanggung beban yang tidak adil karena harus memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anaknya tersebut seorang diri. Padahal lahirnya anak ini juga ada turut andil dari ayah biologisnya. Dengan konstruksi hukum yang demikian, akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak biologis dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum Islam dan sakralitas perkawinan,
Penulis berpendapat bahwa kedepannya, dalam hukum positif di Indonesia perlu dibuat suatu kategorisasi terhadap status dan hak keperdataan anak luar kawin yang diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin kepastian hukum dan agar tidak ada benturan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Kategorisasi ini dapat berbentuk penjabaran jenis hak keperdataan melalui regulasi formal meliputi : nasab, jaminan waris, jaminan perwalian, dan jaminan kesejahteraan. Selain itu, dapat juga diatur mengenai penjabaran kategorisasi anak meliputi : anak sah, anak di luar kawin (nikah siri) dan anak di luar kawin (yang lahir karena perbuatan zina). Hal ini dilakukan agar laki-laki yang menghamili seorang perempuan tidak serta merta terbebas dari kewajiban terhadap anak akibat perbuatannya dan pemenuhan hak sipil anak yang tidak berdosa terkait dengan pembuatan akta kelahiran dapat diakomodir oleh administrasi negara. Selama ini, belum ada pengaturan yang mengakomodir hak-hak anak di luar kawin berdasarkan kategorisasi semacam ini. Namun jika menganalisa lebih dalam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya menjadi salah satu referensi ideal. Sebab fatwa ini tidak memberikan status dan hak keperdataan terhadap anak zina sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun melalui lembaga ta’zir hak-hak keperdataan anak luar kawin dapat terpenuhi dengan pembebanan biaya penghidupan anak dan juga wasiat wajibah untuk anak tersebut. Pemenuhan hak anak secara terbatas ini dapat diimplementasikan dalam putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kearifan dan kebijaksanaan hakim.
KESIMPULAN
Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil).
Keberadaan anak sebagi amanah dan karunia dari ALLAH SWT wajib dijaga dan dilindungi jaminan hak-hak keperdataannya baik oleh orang tua maupun negara. Secara kelahirannya, status anak dapat dibedakan menjadi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (nikah siri), dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (karena perbuatan zina). Terhadap anak sah, mereka memiliki hubungan dan hak keperdataan yang sempurna dari orang tuanya. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (nikah siri) juga dapat memiliki hubungan dan hak keperdataan yang sempurna dari orang tuanya apabila diajukan itsbat nikah orang tua maupun penetapan asal usul anak oleh Pengadilan. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (karena perbuatan zina), secara hukum positif dan hukum islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, disinilah peran penting Pengadilan Agama untuk dapat mewujudkan keadilan sosial melalui konstruksi hukum yang dilakukan oleh hakim dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
[1] Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[2] Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
[3] Trisnawati, Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015, Hlm. 33
[4] Prof Dr Nasaruddin Umar MA, Dilema Nikah Siri - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website (uinjkt.ac.id), diakses 04 Juni 2022 pukul 17:46 WIB
[5] Heru Ramdani, KEDUDUKAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1074 | - A11109182 | Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, diakses 04 Juni 2022 pukul 18:09 WIB
[6] Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam
[7] Lihat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012
[8] Chatib Rasyid, Anak Lahir di luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina, Badilag Net, 2012
[9] Drs. Asrofi, S.H., M.H., Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif, PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM POSITIF (pa-mojokerto.go.id), diakses 4 Juni 2022 pukul 19:30 WIB
[10] Harian Jawa Pos, 28 Maret 2012, hlm. 1
[11] ibid.
[12] Maqashid Syari’ah yang termasuk dalam kategori al-Mashlahah al-Mu’tabarah dharuriyyah yang terdiri dari 5 tujuan agama, yaitu dalam rangka menjaga agama (hifdz ad-diin), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), harta (hifdz al-maal) dan keturunan (hifdz an-nasl). Lihat lebih lengkap di Muhammad Abu Zahrah, tt, Ushul al-Fiqh. Al-Qaqhirah, Dar al-Fikr, Hlm. 220.
[13] M. Nurul Irfan, 2012, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta, Amzah.Hlm. 8-9.
[14] Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
[15] Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
[16] Lihat Pasal 7 ayat (2) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
[17] Lihat Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
[18] Drs. Abd. Gani, M.H., Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif, PA Pekanbaru, 2017, Hlm. 3
[19] ibid.
[20] Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, 2011, Hlm. 150
[21] Drs. Asrofi, S.H., M.H., Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif, PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM POSITIF (pa-mojokerto.go.id), diakses 4 Juni 2022 pukul 19:30 WIB
[22] Muhammad Taufiki, Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah,Jurnal, Ahkam, Jakarta, 2012, Hlm.60
[23] Lihat Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012
[24] A. Manan, 2007, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 83
[25] Rohmawati, Ahmad Rofiq, Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal-Usul Anak (Kajian Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis), Ijtihad IAIN Salatiga, Hlm.11
[26] Arto, A. M, Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta’zir Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama. Badilag Mahkamah Agung RI, 2013, Hlm. 1-26
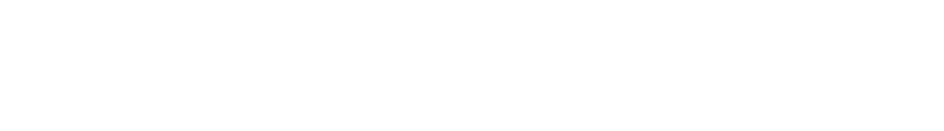












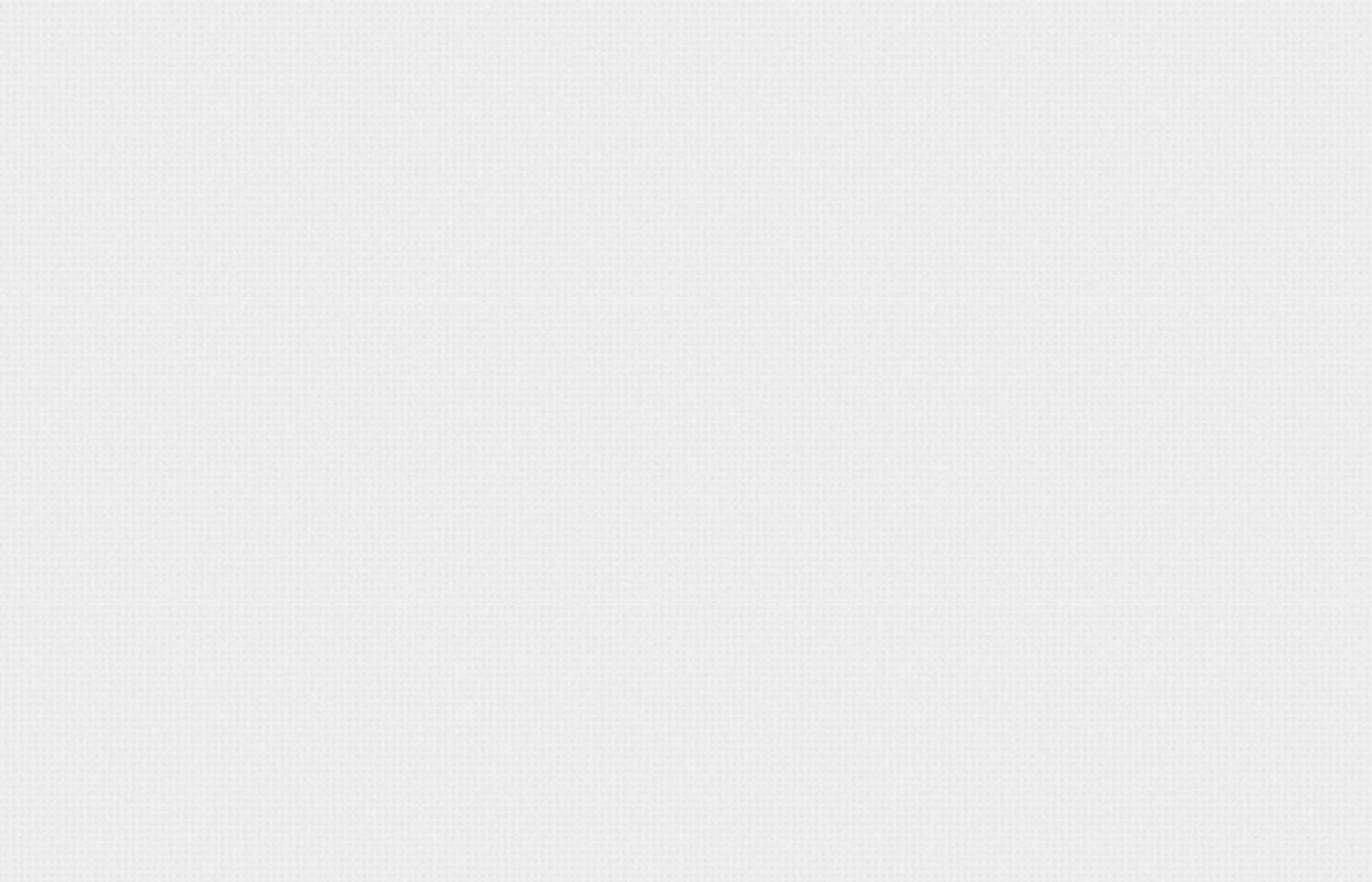









Berita Terkait: