Srikandi di Singgasana Pengadil
Oleh Achmad Fauzi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
Mahasiswa Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Artikel ini dimuat di Harian KOMPAS tanggal 14 Mei 2022

Keterwakilan hakim perempuan di pengadilan menjadi horizon baru perjuangan kesetaraan. Eksistensi srikandi pengadil mendobrak kultur patriarki yang selama ini membelenggu cipta, rasa, dan karsa perempuan dalam urusan domestik.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 hakim perempuan mencapai 28,27% atau mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang berjumlah 26,69%. Data tersebut mengonfirmasi perempuan menjadi bagian dari pelaku pembangunan berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals).
Fenomena baru
Uniknya pengisian jabatan hakim di beberapa negara belakangan ini mengalami fenomena baru yang mendobrak pakem. Amerika Serikat, misalnya, baru saja memilih Ketanji Brown Jackson sebagai hakim agung perempuan pertama dari kulit hitam (Kompas, 8/4). Keputusan tersebut menjadi interupsi zaman bahwa proses pengisian jabatan hakim harus bertumpu pada prinsip meritokrasi dan kesetaraan gender.
Pemerintah Arab Saudi juga menyatakan akan menunjuk wanita sebagai hakim peradilan (www.kompas.tv, 17/1). Keputusan tersebut melampaui pendapat sebagian ulama klasik yang telanjur menempatkan perempuan pada posisi instrumental ketimbang substansial. Dalam kitab Syarhus Sunnah (X/77) Al-Imam al-Baghawi menyatakan para ulama telah sepakat bahwa perempuan tidak layak diangkat menjadi hakim karena harus berhadapan langsung dengan pihak berperkara, sementara perempuan adalah aurat yang tidak mungkin tampil dan melaksanakan banyak urusan.
Pada tahun 1968 Indonesia sudah menabuh genderang kesetaraan gender di ranah kekuasaan kehakiman. Saat terjadi proses transisi orde dari Soekarno ke rezim Soeharto, Sri Widoyati Wiratmo ditetapkan sebagai hakim agung pertama dari kaum perempuan. Amerika Serikat barangkali ketinggalan kereta peradaban dari Indonesia karena baru memiliki hakim agung perempuan pada tahun 1981 bernama Sandra Day O’Connors.
Tahun 1968 menjadi tonggak sejarah keperempuanan di pengadilan karena memberikan ruang bagi hakim perempuan untuk terlibat dalam mengadili perkara. Meskipun intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan kehakiman menjadi postulat politik yang sukar terbantahkan, namun berdasarkan prasangka baik pembangunan di bidang hukum telah memberikan suara kepada kaum yang tak mampu lagi bersuara.
Intrusi kekuasaan politik
Motivasi politik rezim dengan memasukkan kiprah perempuan dalam kekuasaan kehakiman ketika itu bisa dibaca dari dua perspektif. Pertama, politik hukum memang menghendaki kiprah perempuan dalam kancah ketatanegaraan.
Kedua, stigmatisasi perempuan sebagai makhluk tak berdaya menjadi perangkap yang sengaja dipasang kekuasaan politik. Maksudnya, hakim perempuan yang dipersepsikan sosok lemah, gampang dipengaruhi, mudah disetir, bisa dijadikan instrumen gerakan revolusi dan manifesto politik.
Ada tiga model intervensi kekuasaan politik terhadap kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, antara lain: (a) intervensi pemerintah pada awal proses pemeriksaan perkara dengan melibatkan aparat intelijen militer pada kasus-kasus pidana politik; (b) campur tangan penolakan untuk mematuhi putusan pengadilan yang mengalahkan pemerintah; (c) campur tangan melalui labelisasi politis yang merugikan terhadap pihak yang berperkara melawan pemerintah.
Ilusi bahwa hakim perempuan dipersonifikasikan sebagai sosok yang mudah diintervensi, gampang dikendalikan, dan berada di bawah superioritas kekuasaan laki-laki kenyataannya hanyalah fatamorgana. Buktinya, rekam jejak Widoyati sejak menjadi hakim tingkat pertama hingga hakim agung dikenal tegas dan imparsial dari pengaruh apapun.
Ketika mengadili perkara Cosmos yang melibatkan seorang penyelundup, Widoyati berdiri kokoh menolak pesanan Soekarno yang meminta perkara tersebut diadili sebagai perkara subversif dengan ancaman pidana mati. Intrusi kekuasaan politik tersebut disampaikan melalui Ketua MA Wirjono Prodjodikoro. Widoyati menolak keras dengan alasan tindak pidana penyelundupan bukan pidana subversi politik yang memungkinkan dijatuhkannya pidana mati.
Tak mau bertentangan dengan nuraninya, Widoyati meminta agar perkara itu diserahkan kepada hakim lain untuk mengadili. Perkara itu pindah tangan dan hukuman mati pun dijatuhkan. Ketika perkara itu sampai di tingkat Mahkamah Agung, demokrasi terpimpin sudah ambruk (Suparman Marzuki, 2013, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Bunga Rampai Komisi Yudisial, hlm.82-83).
Simbol ketangguhan
Hakim-hakim di seluruh tanah air barangkali mengalami hal serupa dengan variabel intervensi dan tingkat ancaman yang berbeda-beda. Tapi peristiwa yang dialami Widoyati melukiskan ketangguhan kaum feminim. Saat tampil sebagai pengadil ia sangat berdaya dengan keilmuannya, lembut tapi tidak gampang jatuh dalam bujuk rayu, penyayang namun tegas menerapkan hukum tanpa pandang bulu.
Maka itu, Ketua MA Prof. H.M. Syarifuddin mengungkapkan bahwa komposisi hakim yang heterogen dapat memperkaya pendekatan yang seimbang untuk menegakkan hukum dan menerapkan kesetaraan gender. Bahkan, kehadiran hakim perempuan menjadi motor penggerak reformasi peradilan.
Dalam konteks memperkaya hazanah pendekatan kelimuan, hakim perempuan mampu memberikan putusan yang adil, proporsional, profesional, dan memiliki ketajaman sensitivitas gender dalam mengadili perkara-perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
Dalam perkara perdata agama, misalnya, perempuan acap menjadi korban perceraian dan kesewenang-wenangan laki-laki. Perempuan kerap menjadi victim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence), baik kekerasan fisik, mental, dan seksual. Perempuan ditelantarkan suami tanpa nafkah dan hak-haknya pasca-perceraian terbengkalai. Perempuan juga jadi korban perkawinan di bawah umur, sehingga angka kematian ibu dan anak meningkat.
Isu-isu perempuan berhadapan dengan hukum tersebut baru secuil dan membutuhkan kepeloporan serta sensitivitas hakim perempuan. Pendekatan sistem promosi dan mutasi hakim barangkali menjadi jalan prosedural dengan memanfaatkan instrumen SDGs sebagai pandu untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam kepemimpinan peradilan.
Kewenangan KY dan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung juga perlu mempertimbangkan aspek representasi keterwakilan perempuan. Pada tahun 2022, dari 48 hakim agung, baru ada 5 hakim agung perempuan. Stereotype harus dihapuskan karena perempuan juga memiliki kompetensi sebagai pengadil dan memimpin reformasi peradilan.
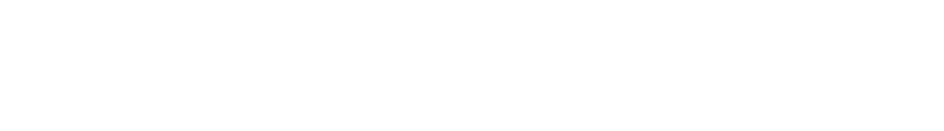












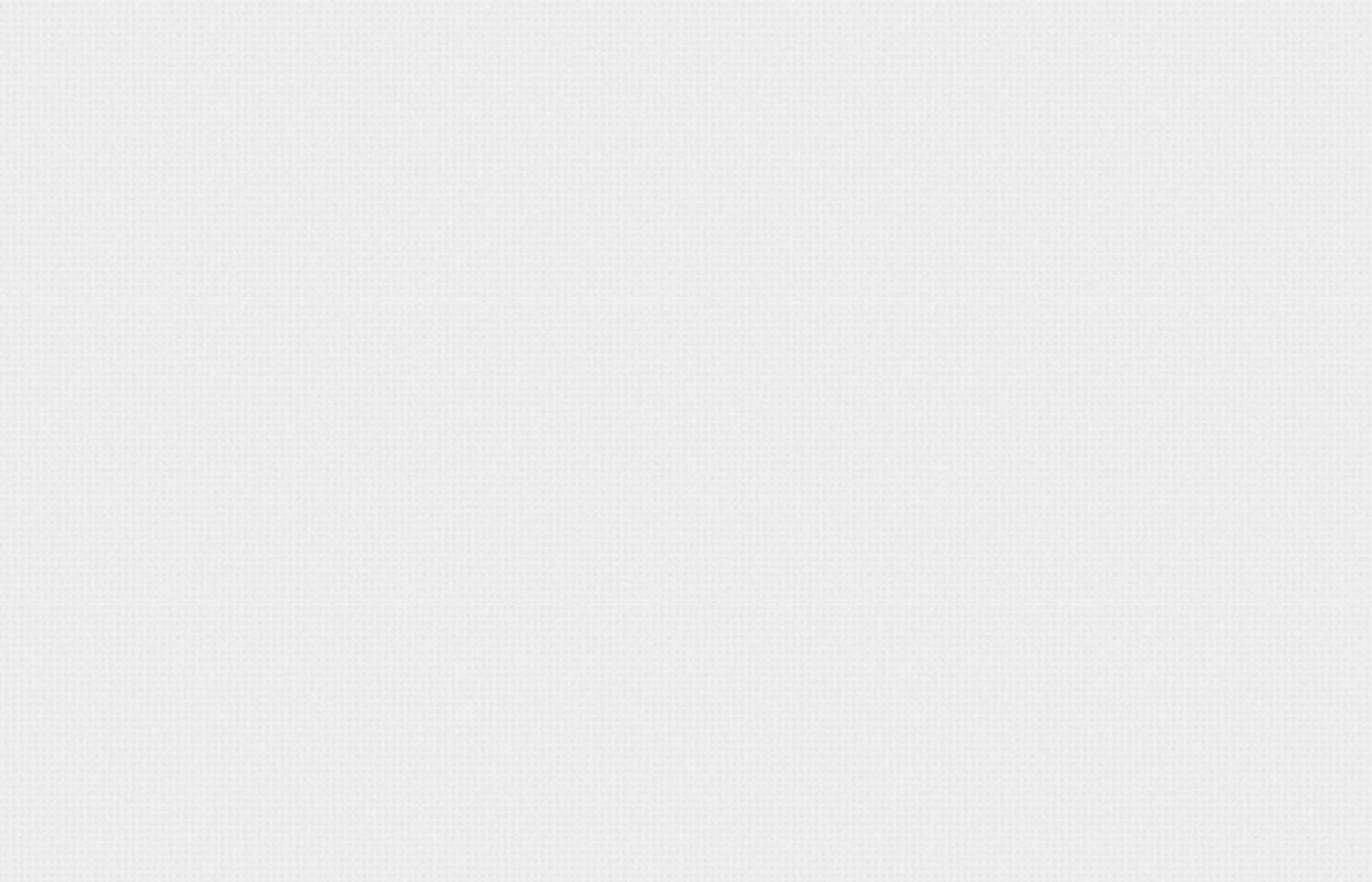









Berita Terkait: