Kepada Siapa Hukum Mengabdi
Oleh Achmad Fausi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo; Mahasiswa Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Artikel ini dimuat di Harian Umum KOMPAS tanggal 31 Januari 2022
Korupsi yudisial kembali menyeruak. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pengacara, oknum hakim, dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka diduga terlibat skandal suap penanganan perkara. Masih adakah keadilan dan moralitas penegak hukum di negeri ini? Kepada siapa hukum memihak dan bekerja?
Trajektori kekuasaan kehakiman
Masa Orde Lama eksistensi lembaga peradilan cukup tragis karena dijadikan instrumen gerakan revolusi dan manifesto politik. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara, dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Hal ihwal berkaitan dengan penataan organisasi, manajemen administrasi, dan finansial pengadilan di bawah kendali departemen (eksekutif).
Rezim Orde Baru nasib pengadilan masih mempertahankan konsep dua atap. Bahkan, Ketua MA sebagai pemimpin tertinggi lembaga yudikatif berdasarkan tingkat jabatan dan protokoler disetarakan dengan jabatan menteri.
Era reformasi bergulir dan sistem ketatanegaraan dirombak ulang. Berdasarkan TAP MPR No. X/MPR/1998 yang ditindaklunjuti dengan pemberlakuan UU No. 35 Tahun 1999, semua hal ihwal berkaitan dengan urusan organisasi, finansial, dan administratif pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Pemberlakuan beleid tersebut berjalan efektif terhitung sejak tahun 2004 yang kemudian dikukuhkan dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada era reformasi, kendati telah menertibkan sistem ketatanegaraan dan membagi secara jelas demarkasi tiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), namun tak dimungkiri sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka masih dibayang-bayangi menurunnya kualitas moral aparat peradilan. Jika dahulu ancaman intervensi rezim menjadi problem serius yang dihadapi lembaga yudikatif, namun kini ancaman itu berasal dari dalam lantaran krisis integritas makin mengancam.
Menurunnya kualitas moral dalam hukum mengingatkan kita pada sebuah kredo klasik: ‘Hukum hampa tanpa moral’. Kredo tersebut kemudian dikukuhkan dalam irah-irah putusan hakim yang berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Irah-irah/titel eksekutorial merupakan kristalisasi dari nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum agar dijadikan pandu nurani bagi hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan bersendikan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang notabene memberi mandat kepada pengadil di muka bumi.
Irah-irah putusan hakim dalam lintasan sejarah mengalami dinamika konseptual. Sejarah mencatat, pengadilan pernah menggunakan kepala putusan “Atas Nama Ratu/Raja” atau In naam der Koningin. Kemudian berubah menjadi “Atas Nama Negara”. Karena hukum rawan menjadi alat politik dan pelanggengan kekuasaan, akhirnya kepala putusan berubah menjadi “Atas Nama Keadilan” (In naam der Gerechtigheid). Kepala putusan yang berlaku saat ini adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Bismar Siregar, 1983).
Irah-irah tersebut merupakan konsepsi ideal yang dirumuskan oleh para ahli hukum karena secara etis-filosofis menggambarkan fungsi suatu hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan. Di sisi lain, irah-irah tersebut mengandaikan proses penegakan hukum berjangkar pada moralitas. Sehingga secara aksiologis sangat jelas untuk apa hukum ditegakkan dan kepada siapa putusan hakim harus dipertanggungjawabkan.
Dalam kerja penegakan hukum, hakim harus mampu mempertanggungjawabkan profesinya sebagai officium nobile. Sehingga hukum benar-benar bekerja atas nama Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka itu, kerja penegakan hukum sedapat mungkin dikawal oleh filsafat moral karena potensi penyelewengan hukum sangat besar.
Berdasarkan catatan hukuman disiplin dari Badan Pengawasan MA, pada tahun 2021 sebanyak 250 hakim dan aparatur peradilan dikenai sanksi ringan, sedang, hingga berat. Sebagian pelanggaran berkaitan dengan jual beli perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa hukum kita masih bisa dibeli. Harganya murah. Semurah harga diri penjualnya. Karena sudah dibikin bisnis tentu jaringannya rapi. Dilengkapi pula tingkat keamanan dalam beroperasi. Supaya tak terendus, tawar-menawar harga acap menggunakan bahasa sandi. Maka itu, MA terus mendorong pemberantasan nalar koruptif yang dimulai dengan memperkuat bangunan moral, aspek kepemimpinan, dan manajemen peradilan.
Keteladanan moral dimulai dari pucuk pimpinan sebagai role model. Kemudian bekerja keras melakukan pembinaan mental dan kode etik profesi, bersinergi menyatukan seluruh elemen aparat peradilan yang memiliki integritas baik agar tak terkontaminasi, dan konsisten menerapkan reward dan punishment. Beri penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Bertindak tegas bagi yang merusak citra lembaga. Jika tak bisa dibina, lebih baik “dibinasakan” daripada meracuni yang lain.
Persoalan korupsi yudisial ini sangat serius karena memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam logika publik menganut majas pro toto. Satu orang berbuat tercela semua tercoreng kena getahnya. Bagi pencari keadilan, perbaikan integritas nomor satu yang tak bisa ditawar. Hukum harus bermoral dan tak boleh tegak di atas pilar kecurangan.
Menurut teori hukum alam, hukum, moral, dan keadilan dipandang sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ronald Dworkin, salah seorang penganut mazhab hukum alam modern, dalam teorinya menyebut law as integrity. Maksudnya adalah hukum yang baik adalah hukum yang memiliki moralitas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Teori tersebut relevan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan hukum bekerja untuk melayani manusia. Bukan sebaliknya, manusia yang melayani hukum. Kedua teori tersebut barangkali menjadi garansi bagi para pencari keadilan bahwa hukum (seharusnya) bekerja untuk kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

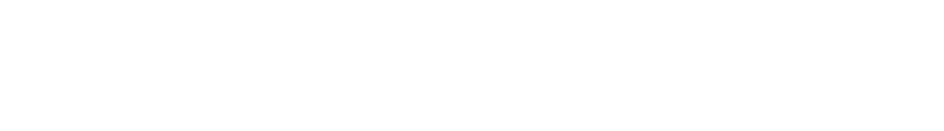












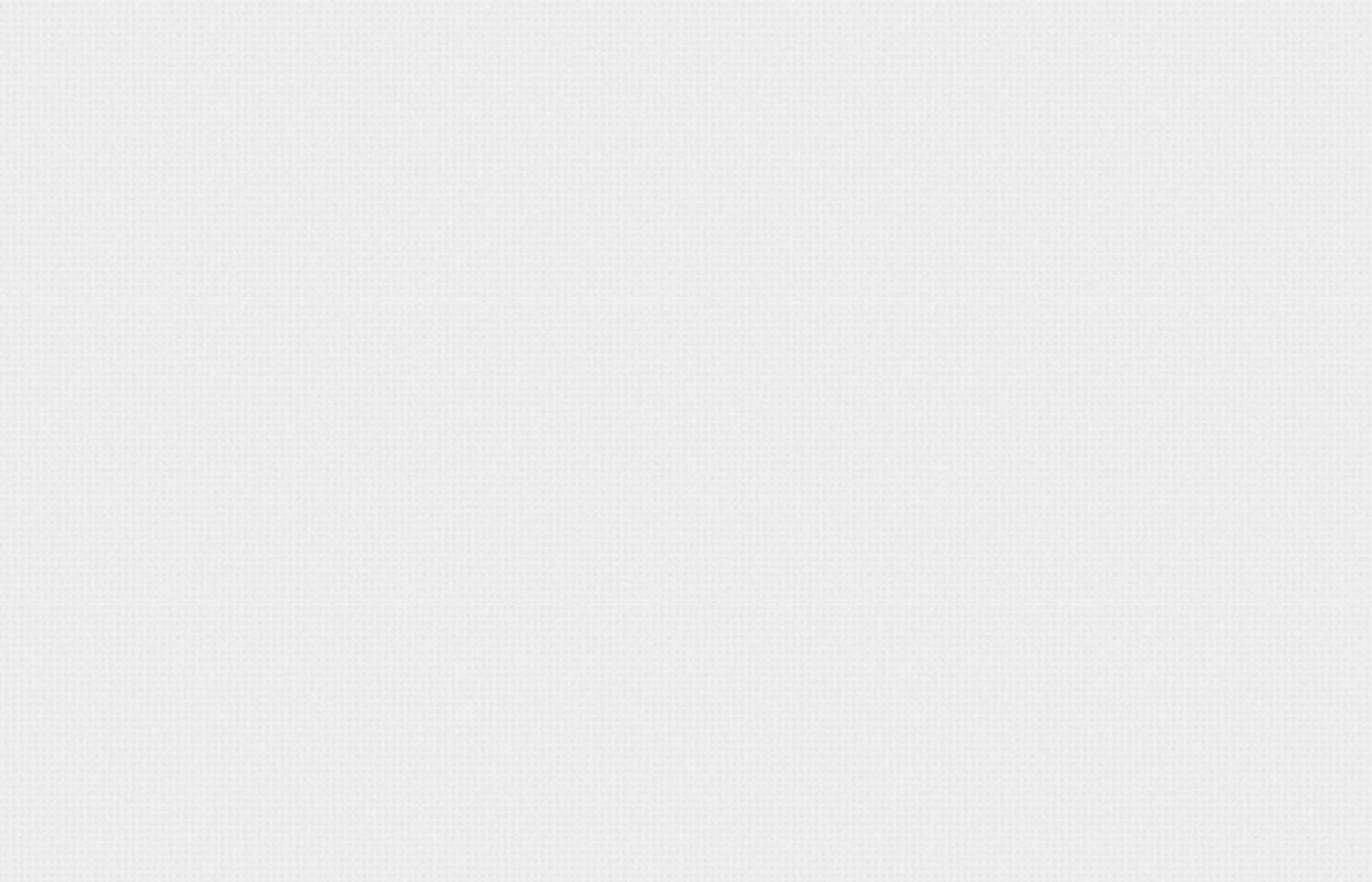









Berita Terkait: