Intrusi Politik dalam Seleksi Hakim Agung
Oleh Achmad Fauzi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
Mahasiswa Program Doktor FIAI UII Yogyakarta
Artikel ini dimuat di Koran Tempo tanggal 8 April 2022

Komisi Yudisial menyeleksi calon-calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang nantinya dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Hakim agung bukanlah jabatan politik yang terikat periodisasi. Tapi residu determinasi kekuasaan politik dalam pengisian jabatan hakim agung bisa mencemari kemurnian hukum.
Menurut teori hukum murni (pure theory of law) yang dicetuskan Hans Kelsen (1881-1973), hukum harus berupaya mensterilkan obyek penjelasannya dari hal ihwal yang tidak bersangkut-paut dengan hukum, termasuk membersihkan hukum dari anasir politik. Bagaimana sebaiknya perekrutan hakim agung dilakukan?
Kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan dalam seleksi calon hakim agung menunjukkan betapa intrusi kekuasaan politik telah bertransformasi menjadi forum yang kental akan nuansa politis. Akibatnya, keputusan yang diambil selalu dapat dibaca sebagai bagian dari aktivitas politik yang menyimpang dan mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi (Thohari, 2004).
Tidak dapat dimungkiri bahwa DPR merupakan representasi anggota partai politik yang terfragmentasi ke dalam fraksi-fraksi yang saling berseberangan dalam bingkai koalisi dan oposisi. Persetujuan yang mereka ambil merupakan jelmaan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, tidak terkecuali untuk mengamankan perkara korupsi yang hingga kini semakin menggurita dalam lingkup kekuasaan politik.
Akibatnya, calon hakim agung yang memiliki reputasi baik, terampil, mumpuni, dan berintegritas tinggi kandas karena tidak memiliki kedekatan politik di DPR. Hal itulah yang menurunkan animo masyarakat untuk menjadi hakim agung. Begitu pula calon hakim agung yang lulus akan berada di bawah bayang-bayang politik jika persetujuannya didasari politik transaksional.
Alasan lainnya adalah sebagian anggota DPR tidak berlatar belakang hukum. Tapi, dalam menjalankan kewenangan, mereka masih melakukan uji publik terhadap hakim karier yang sudah puluhan tahun malang melintang menangani perkara ataupun hakim non-karier yang berkecimpung di bidang hukum. Praktik ketatanegaraan yang demikian menjadi rancu karena segala etape uji kompetensi, rekam jejak, dan uji kelayakan sudah dilakukan secara komprehensif oleh Komisi Yudisial, yang notabene merupakan lembaga non-politik yang dibentuk konstitusi sebagai penunjang kekuasaan kehakiman.
Jika DPR ditahbiskan sebagai manifestasi dari keterwakilan aspirasi politik rakyat, tentu daulat rakyat mendambakan hakim agung yang disetujui memiliki kompetensi teknis yudisial yang mumpuni, berintegritas tinggi, dan memiliki wawasan hukum yang luas. Menjadi sangat sulit bila tolok ukur, tim penguji, dan bobot substansi uji publik tidak dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya serta independen dari urusan politik. Intrusi kekuasaan politik dalam jangka panjang berimplikasi hukum pada supremasi kemerdekaan personal, kemerdekaan substantif, dan kemerdekaan kolektif kekuasaan kehakiman.
Proses perekrutan dan persetujuan calon hakim agung merupakan hulu dari segala pembicaraan tentang reformasi kekuasaan kehakiman. Jadi, proses perekrutan dan persetujuan hakim agung harus dipastikan steril dari berbagai konflik kepentingan ataupun mekanisme politik yang merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari (2005) memberikan parameter bahwa merdeka atau tidaknya lembaga kehakiman dapat dilihat dari apakah kekuasaan kehakiman mempunyai ketergantungan terhadap lembaga lain selain dalam urusan mengadili perkara yang memang sudah menjadi tugas dan wewenangnya. Di samping itu, apakah lembaga tersebut mempunyai hubungan hierarkis secara formal sehingga bisa ikut campur dan mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Di negara-negara dengan model pemerintahan presidensial dan sistem politik demokrasi seperti Indonesia, efektivitas pelaksanaan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman cukup problematik ketika relasi tiga cabang kekuasaan negara—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—bertemu dalam satu bejana ketatanegaraan. Dalam praktik ketatanegaraan modern, hal ini meniscayakan satu kekuasaan negara tidak bisa terlepas secara mutlak dari kekuasaan lain.
Ketika suatu organ negara memegang kekuasaan secara mutlak tanpa adanya saling kontrol dan saling mengimbangi, hal itu berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka, fungsi checks and balances diberlakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum. Dalam praktiknya, fungsi itu menyimpan karakter kekuasaan politik yang lebih hegemonik terhadap kekuasaan yudikatif. Setidaknya potret trajektori kekuasaan kehakiman pada tiap rezim yang acap dikooptasi oleh kekuasaan politik menjadi fakta politik yang sulit terbantahkan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif sangat berpengaruh terhadap kemurnian asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif-tidaknya penegakan hukum bergantung pada trigatranya: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan adanya mekanisme politik dalam pelaksanaan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung, hal ini berimplikasi hukum pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga struktur, substansi, dan budaya hukum tidak dapat ditegakkan secara ideal.
*Penguatan Komisi Yudisial*
Penguatan wewenang Komisi Yudisial sebagai otoritas tunggal dalam menentukan kelulusan calon hakim agung mutlak dilakukan demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari semesta pengaruh kekuasaan-kekuasaan lain. Pertama, Komisi Yudisial berperan memutus mata rantai persoalan teknis kekuasaan kehakiman yang semula sangat birokratis dan tidak merdeka karena melibatkan banyak cabang kekuasaan. Kedua, kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman menjadi instrumen untuk menjauhkan proses perekrutan calon hakim agung dari kepentingan-kepentingan politik.
Pembentukan Komisi Yudisial merupakan “jihad konstitusional” yang bertujuan agar hukum tidak tercemar oleh berbagai anasir di luar hukum. Dengan begitu, hakim agung, dalam menjalankan wewenangnya nanti, tidak terpengaruh oleh bujuk rayu, ancaman, dan intervensi dari pihak lain.
Ide ini merupakan bentuk hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) supaya Mahkamah Agung benar-benar menjadi peradilan yang agung. Tentu dibutuhkan politik hukum dari kekuasaan politik untuk meninjau ulang pengaturan dalam pengisian jabatan hakim agung agar lebih berorientasi pada filosofi negara hukum yang menjamin kemurnian prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.
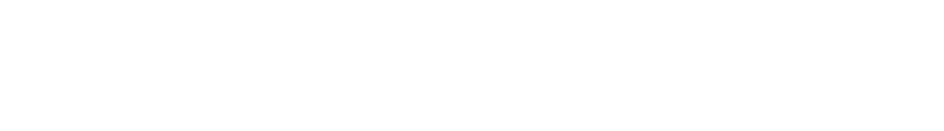












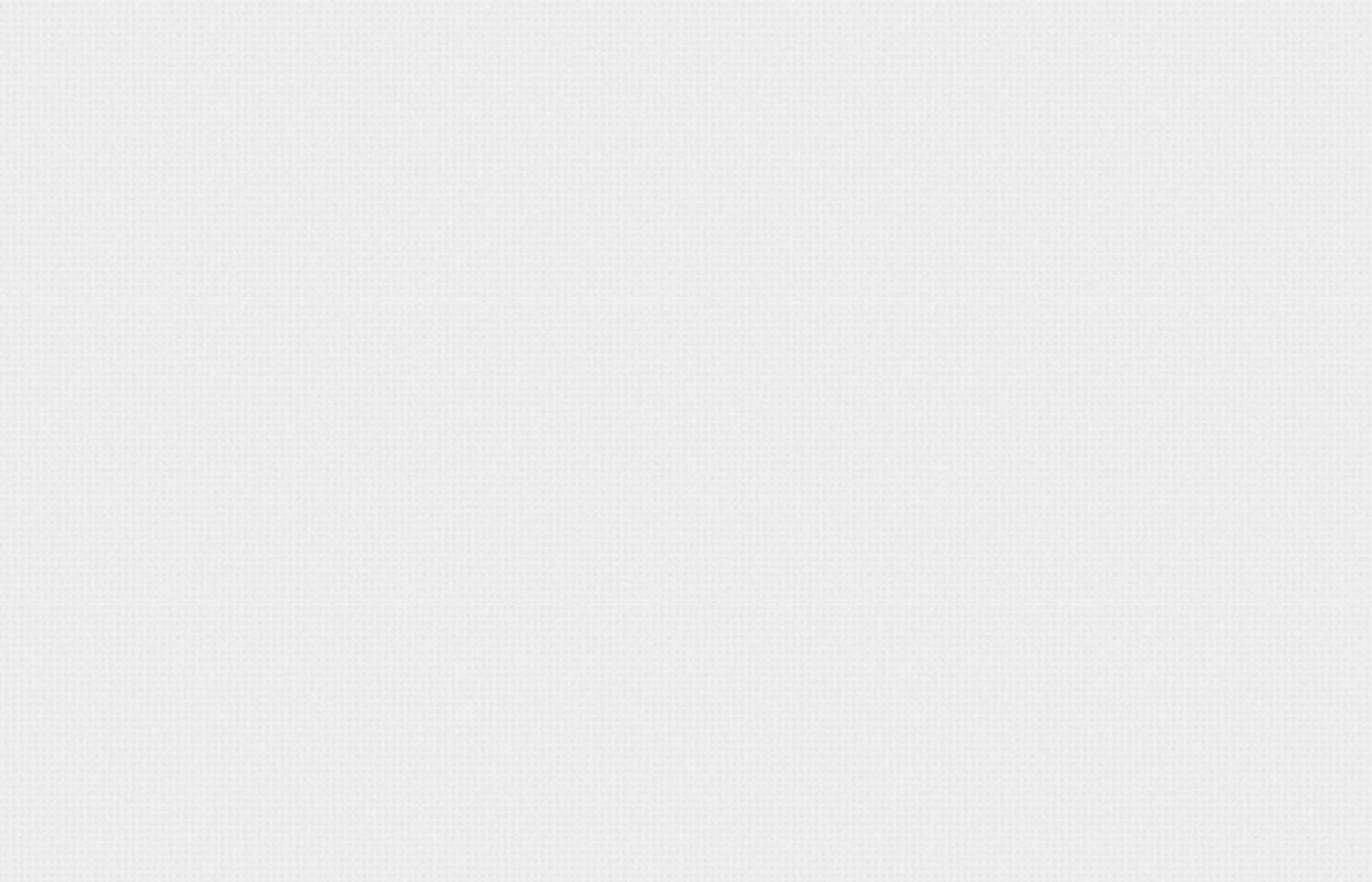









Berita Terkait: