Quo Vadis RUU Jabatan Hakim
Oleh Achmad Fauzi
Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

Jabatan hakim transendental. Menembus langit ketujuh. Tugasnya berat menjalankan sebagian kekuasaan Tuhan. Menjadi pengadil di muka bumi. Pertanggungjawaban profesinya juga eksplisit tertera pada mahkotanya: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makanya, ancaman siksa bagi hakim tak adil di akhirat sangat berat. Misalnya, disembelih tanpa menggunakan pisau, satu kakinya menginjak neraka, dan masih banyak ancaman mengerikan lainnya.
Meski tugas hakim berat dan berpredikat Yang Mulia namun hingga kini belum ada aturan yang secara khusus mengatur jabatan hakim. Aturan tentang jabatan hakim masih menyebar dan parsial dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Padahal, sudah tujuh puluh tahun Indonesia merdeka secara politik dan 18 tahun roda pedati reformasi hukum bergulir. Karena itu, sudah semestinya keputusan politik DPR memasukkan RUU Jabatan Hakim dalam Prolegnas.
Sejatinya pada tahun 2019 DPR telah memasukkan RUU Jabatan Hakim dalam daftar Prolegnas. Namun, dinamika politik bertegangan tinggi, membuat RUU Jabatan Hakim terkubur dalam tumpukan kertas kerja yang tak tahu sampai kapan diprioritaskan. Melihat urgensi dan kepentingan masa depan hukum, sudah sepatutnya DPR segera mengambil peran dan porsi untuk membahas RUU Jabatan Hakim. Beberapa persoalan krusial yang membelenggu independensi hakim perlu diinventarisir dengan mendengarkan masukan dari banyak pihak. Sehingga dasar filosofis dan politik hukum yang melatari terbentuknya undang-undang tersebut benar-benar berangkat dari kajian mendalam tentang kedudukan hakim dan memberikan jalan keluar bagi pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.
Pengesahan RUU Jabatan Hakim secara faktual menjadi conditio sine qua non. Sejak UUD 1945 diamandemen kedudukan kekuasaan kehakiman mengalami perubahan fundamental. Kedudukan lembaga peradilan semakin kuat karena mendapat garansi konstitusi. Hal ini dapat ditilik dari perubahan frasa fungsi pengadilan sebagai “pelaksana” menjadi “pelaku” kekuasaan kehakiman. Secara maknawi perubahan frasa tersebut diartikan bahwa pengadilan adalah subyek yang memiliki otoritas otonom dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implikasinya, hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman juga harus merdeka dari campur tangan pihak manapun.
Namun, persoalannya, hingga saat ini kemerdekaan hakim masih terbelenggu oleh statusnya yang “berkelamin” ganda. Meski dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara menyebut hakim sebagai pejabat negara, namun atribut kepegawaian, mekanisme perekrutan dan pemberhentian, jenjang kepangkatan, sistem penggajian dan protokoler hakim masih mengikuti pola PNS. Karena itu, status hakim sebagai pejabat negara perlu afirmasi.
Pasal krusial
Pada tahun 2019 Badan Legislasi DPR memang sempat menyetujui secara bulat RUU Jabatan Hakim setelah melewati etape proses harmonisasi antarperaturan perundang-undangan dan pemantapan konsepsi. Namun terlepas dari tarik ulur penetapan RUU Jabatan Hakim sebagai Prolegnas, ada beberapa pasal krusial yang perlu dikritisi dalam draf yang beredar karena spirit filosofisnya telah keluar dari amanat UUD 1945.
Pertama, terkait gagasan kocok ulang hakim agung setiap lima tahun sekali. Pasal 32 ayat (1) RUU Jabatah Hakim menyatakan hakim agung memegang jabatan selama lima tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap lima tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh KY. Selanjutnya pada ayat (2) hasil evaluasi diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan diangkat kembali sebagai hakim agung.
Nalar legislasi semacam ini tentu sebuah sesat pikir karena jabatan hakim agung dipersepsikan sebagai jabatan politis. Padahal sejak awal konstitusi sudah menggariskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Jika pasal tersebut tidak segera dicabut akan menimbulkan preseden buruk sebagaimana halnya terjadi pada era Orde Baru. Kekuasaan lain bisa turut campur tangan terhadap kekuasaan yudikatif melalui selubung evaluasi kinerja yang celakanya sudah masuk pada ranah teknis yudisial. Jika rongrongan terhadap kemerdekaan hakim melalui politik legislasi tersebut tidak segera dihentikan maka ke depan kita akan saksikan betapa besarnya arus politik dalam mempengaruhi kerja yudikasi. Hakim agung akan banyak tersingkir karena tidak memiliki kedekatan politik dan atau enggan menjalankan pesanan politik.
Jika akuntabilitas peradilan dijadikan dalil primer untuk mengevaluasi hakim agung tentu bukan cara yang tepat. Evaluasi ranah teknis yudisial melanggar norma universal tentang independensi peradilan. Hal ini dapat ditilik dalam Basic Principles on the Independence Judiciary yang diadopsi dalam Kongres VIII tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offender yang diadakan di Milan tanggal 26 Agustus - 6 September l985. Ketentuan tersebut kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB Resolution 40/32 of 29 November l985 and 40/146 of 13 Desember l985. Beberapa ketentuan dalam Basic Principles tersebut antara lain sikap tidak memihak, tanpa kendala atau pengaruh yang tidak pantas, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun atau dengan alasan apapun.
Kedua, soal pengurangan batas usia hakim. Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa hakim diberhentikan secara hormat karena telah berusia 60 tahun (hakim tingkat pertama), 63 tahun (hakim tinggi), dan 65 tahun (hakim agung). Pengurangan batas usia hakim tersebut sangat drastis dibandingkan aturan sebelumnya. Hal ini bentuk kemunduran berfikir karena gagasan tersebut justru memangkas bagian dari kesejahteraan hakim. Tugas hakim tidak memanggul senjata sehingga tidak relevan dilihat dari sisi fisiknya. Hakim adalah primus interpares, manusia unggul yang memiliki tingkat kearifan dan kebijaksanaan dinamis seiring pertambahan usianya.
Pola pembinaan
Selain persoalan-persoalan di atas, pembinaan hakim adalah elemen penting yang juga perlu diatur secara komprehensif dalam RUU Jabatan Hakim. Pembinaan meliputi penempatan hakim, peningkatan kapasitas keilmuan dan integritas, evaluasi kinerja, mutasi dan promosi.
Penempatan hakim, misalnya, di samping memperhatikan kebutuhan lembaga hendaknya mengutamakan peningkatan kapasitas keilmuan. Berdasarkan prinsip pemerataan, hakim yang terlalu lama tugas di daerah perlu dimutasi ke tempat yang memiliki sarana pendidikan memadai. Sehingga penerapan sistem reward and punishment bisa diterapkan secara tepat, adil dan linear dengan program peningkatan mutu hakim.
Peningkatan integritas sebagai perisai hakim melalui desain pembinaan yang baik. Kedudukan dan fungsi KY sebagai pengawas etik harus diperkuat. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa korupsi yudisial telah menjadi bercak hitam yang terus terjadi dan merusak citra lemaga peradilan. Oknum pengadilan kerap menjadi target operasi tangkap tangan KPK karena tersangkut jual beli perkara.
Ombudsman RI berdasarkan hasil investigasinya selama 1 Januari 2014 - 31 Maret 2016 menemukan masih banyak praktik mafia yang menjanjikan dapat memenangi perkara dengan imbalan uang sekitar Rp25 juta-Rp80 juta. Temuan tersebut menjadi cacatan penting agar langkah preventif perlu diprioritaskan. Sebab, persoalan utama reformasi lembaga peradilan bukan lagi terletak pada kecakapan profesional, melainkan karena krisis integritas.
Hak keuangan
Hak keuangan hakim sebagai pejabat negara juga menjadi isu yang penting diperhatikan oleh DPR. Meski tidak ada penelitian sahih yang mengemukakan korelasi positif antara penaikan penghasilan dengan tingkat korupsi, namun kesejahteraan juga merupakan salah satu hal yang elementer.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung memang telah mengatur hak-hak keuangan hakim, namun belum semuanya terealisasi. Mulai dari jaminan keamanan, protokoler, dan jaminan kesehatan.
Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR pada Rabu (2/6) menceritakan betapa hakim masih ada yang tinggal di tempat terpencil. Fasilitas seadanya dan jauh dari keluarga. Mereka harus menyeberang pulau naik kapal menuju tempat kerja. Bahkan ada yang berbulan-bulan tidak pulang. Yang memprihatinkan banyak hakim meninggal tanpa didampingi keluarga. Karena itu, desain besar pengesahan RUU Jabatan Hakim merupakan langkah politik yang harus diprioritaskan oleh DPR agar ke depan hakim-hakim di Indonesia memiliki status yang jelas, hak-haknya terjamin, sehinga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak lagi memikirkan persoalan-persoalan di atas dan lebih fokus mengadili perkara dengan melahirkan putusan-putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
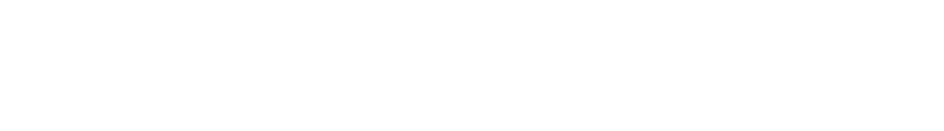












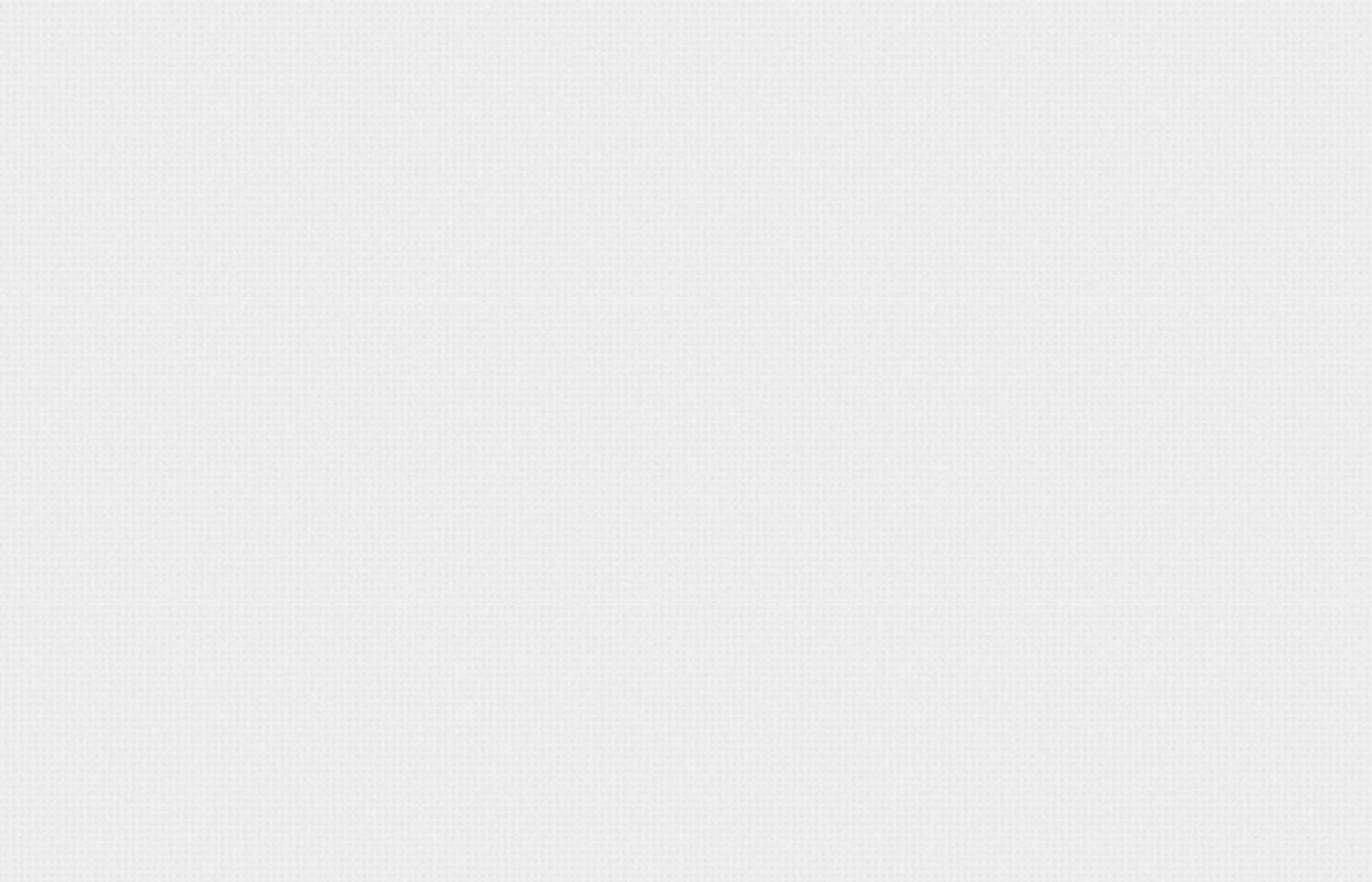









Berita Terkait: